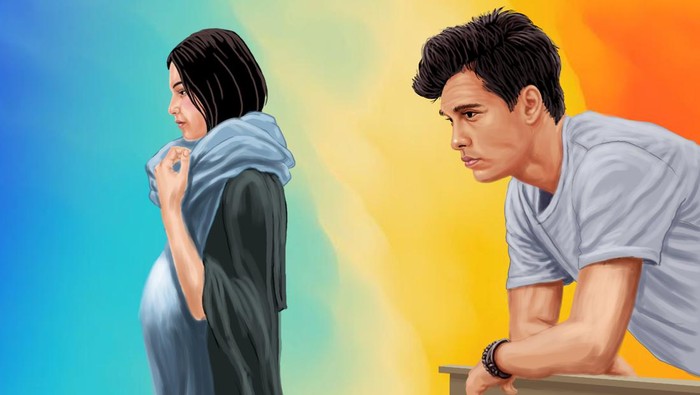Bastian
Namanya Nayanika. Penyihir bermata indah yang selalu membawaku terbang dari lantai ke-32, kamar apartemenku yang sungguh sepi dan dingin, tepat menuju hamparan sorot lampu Ibu Kota yang menyala bagai jutaan kunang-kunang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mengapa kau tak pernah melompat?" tanya dia dari ujung telepon.
"Dari lantai ke-32 ini? Menurutmu apa sudah saatnya aku mati?" tanyaku keheranan dan ikut tertawa ketika mendengarnya tergelak. Tawa gadis itu sungguh menular.
Nay memang selalu begitu. Awalnya kupikir dia gadis aneh dengan segala pemikiran ekstremnya, tak pernah di tengah-tengah. Dan semuanya itu gara-gara buku yang ia baca. Salah satunya sehabis ia memberi materi menulis berita untuk pegawai KUA.
"Kau bilang apa?" tanyaku waktu ia selesai bercerita.
Bukannya aku tak mendengar apa yang ia katakan, kupikir lebih tepatnya aku merasa begitu geli karena menyadari sekali lagi bahwa dia memang sungguh-sungguh gadis yang ekstrem. Tentu saja tak kukatakan pendapatku itu padanya.
Di hadapan puluhan laki-laki pegawai KUA (kupikir laki-laki memang selalu mendominasi di bidang apa pun, apalagi di instansi pemerintahan) Nay lagi-lagi mengeluarkan pikiran ajaibnya.
Dan memang sudah menjadi gayanya yang tak pernah ragu mengeluarkan isi kepala, tanpa basa-basi pula. Gaya yang tak mungkin kuterapkan dalam pekerjaanku di perbankan yang sangat formal dan penuh dengan senyum palsu korporasi. Membayangkannya saja aku tak berani.
"Kalian petugas KUA kenapa selalu melarang para suami-istri itu bertengkar? Apa kalian hendak menambah jumlah kasus perceraian yang sudah begitu tingginya di muka Bumi ini atau setidaknya rumah tangga yang depresi dengan kondisi istri yang selalu diam terkendali?" tanya Nay yang seketika itu juga berhasil mengheningkan kelas, membungkam pandangan meremehkan para laki-laki pada sosok gadis mungil di depan mereka, berubah menjadi pandangan kebingungan.
Tepat seperti itulah kali pertama aku bertemu dengannya. Pandangan meremehkan dan langsung kusesali tak lama setelah ia berbicara. Kelas menulis esai dengannya adalah kelas terbengong yang pernah aku ikuti.
Aku masih ingat betul bagaimana pertemuan pertama kami berlangsung. Awal pandemi yang memaksa orang-orang harus bersembunyi di rumah masing-masing membuat kamarku di ketinggian ini terasa lebih mengurung.
Jakarta sangat gelap dan murung. Kupikir aku akan segera berhalusinasi jika hidupku selalu berkutat pada angka-angka yang minus, ketakutan, ketidakpastian, dan ratusan kabar burung yang datang dan pergi. Aku tak membayangkan diriku segera muncul di media massa dengan judul yang sungguh tak enak. Direktur bank mencoba bunuh diri karena depresi. Harus ada aktivitas yang membuatku lupa sejenak tentang betapa sialnya hidup ini.
Kelas menulis esai dengan Zoom di sebuah kota yang jauh dari tempatku tinggal adalah pilihan teracak yang pernah kubuat. Pematerinya masih sangat muda, Nayanika namanya. Dia cantik, bahkan menurutku cantik sekali, minus make up tebal yang jadi pemandangan harianku.
Di leaflet yang kupandangi lekat, gadis itu tampak tersenyum lebar seakan tak pernah punya masalah dan jelas dia punya otak encer karena ini bukan acara clubbing atau parade baju kan? Jadi kenapa tidak kucoba saja?
Dia minta dipanggil Nay di kelas kecil kami dan kami semua setuju. Bonus kelas ini adalah menatap wajah cantik Nay, sepaket dengan suara kecilnya, yang kupikir lebih mirip mahasiswa magang di kantorku ketimbang jurnalis. Cara lumayan jitu menghabiskan dua jam untuk membunuh kebosanan. Aku tidak menyesali keputusanku.
Nay membagi foto Tara Basro dengan branya yang sempat menjadi kontroversi lalu meminta pendapat kami. Kelas ramai sekali. Dari menyalahkan para lelaki karena terlalu bernafsu, foto tak pantas, Tara terlalu seksi, hingga misoginis. Semua peserta merasa benar dan Nay memang tidak menyalahkan salah satu pun dari kami sebagai bentuk kebebasan berpendapat.
Tapi, dia menyindir kami dengan beberapa kalimat yang membuatku malu seketika.
"Teman-teman pernah merasakan ASI kan? ASI dari payudara ibu. Kenapa teman-teman selalu memandang payudara sebagai objek keindahan wanita? Tidak ingatkah teman-teman kalau payudara itu adalah penyambung hidup kalian?"
Ah, Nay aku rindu sekali padamu. Sedang apa kamu sekarang dan bagaimana harimu?
Aku cek lagi ponsel dan tidak ada pesan apa pun darimu. Sudah beberapa minggu seperti ini dan jelas itu tak seperti biasanya. Semenjak kelas itu, Nay sebenarnya sudah menjadi bagian dari hidupku.
Entah bagaimana aku selalu berusaha agar bisa terhubung dengannya. Menyapanya, mengajaknya bicara, mengiriminya buku-buku yang ia suka, menanyakan harinya, apa pun aku lakukan agar kami bisa berkomunikasi. Kalau kuingat-ingat lagi, aku sempat berubah menjadi jurnalis buruk yang selalu banyak bertanya tentang hidupnya. Stok pertanyaanku tiba-tiba melimpah.
Namun, aku beruntung. Meski aku sangat artifisial menurut dia, kupikir Nay juga telah berubah menjadi narasumber yang sama barbarnya. Gadis itu selalu memberikan jawaban panjang saat aku bertanya dan kami pada akhirnya terjebak dalam percakapan berjam-jam lamanya. Itu adalah awal sebelum akhirnya kami menjadi saling bertanya, saling menyapa, saling bercerita, dan saling membutuhkan.
Nay adalah gadis ekspresif. Banyak cerita, banyak tertawa, dan banyak juga air mata. Mungkin dia sudah memindah jurnal hariannya ke Whatsapp-ku. Tentu saja itu menyenangkan. Pandemi terlupakan dan akhirnya perlahan kurasa pandemi juga bisa menyenangkan semenjak aku mengenal Nay.
Aku membuka korden kamar lebih lebar dan melihat lagi kerlip lampu kota favorit Nay dengan perasaan kacau. Samar-samar kudengar suaranya.
"Mengapa kau tak pernah melompat?"
Entah kenapa mengingat pertanyaan itu sekaligus melihat begitu indahnya Jakarta dari ketinggian ini membuat dadaku terasa sesak seketika. Sebuah kekhawatiran menjalar pelan-pelan. Bagaimana jika Nay hilang dari hidupku? Sanggupkah aku melewatkan hari-hariku tanpa keajaiban yang dia berikan cuma-cuma? Apakah aku pantas untuknya? Dan bagaimana agar aku bisa layak baginya?
Suara hati kecilku, yang selama ini kutimbun dalam-dalam, keluar begitu saja waktu malam merambat menuju pagi. Beberapa hari ini aku memang susah tidur.
"Nikahi saja dia, Bas. Ya, menikah. Kau dengar kan? Nikahi saja Nay. Ikat dia, Bastian." Begitulah isi hatiku yang begitu berisik hingga aku merasa tak punya pilihan.
Dan akhirnya itulah yang akan kulakukan. Aku menarik napas panjang, membulatkan tekat. Besok siang aku akan ke Solo, menemui Nay, dan memintanya menjadi istriku. Semoga saja dia mau. Sebuah doa kukirim ke langit, berharap upaya terakhir menghubunginya itu tidak terlambat. Aku tak mau lagi pertanyaan melompat dari lantai ke-32 selalu mengganggu kewarasanku.
"Bagus, Bas!" kata hati kecilku lagi. Barulah mataku terpejam setelah berhari-hari nyalang menyala.
Nayanika
Aku tidak pernah punya cita-cita menikah, memikirkannya pun tak pernah karena memang kupikir itu bukan sebuah cita-cita. Terikat adalah kondisi mengenaskan. Terikat lama tentu akan semakin menimbulkan banyak luka. Jadi bagaimana sebenarnya gagasan menikah itu bisa menjadi dambaan banyak orang?
Yang lebih mengerikan lagi, bagaimana jika luka itu secara konstan ditimbulkan satu orang saja? Saat kau berani mencintai seseorang, itu berarti kau secara sadar dan siap akan melukainya juga pada suatu saat nanti. Itu satu paket kan, kau tak bisa memilih salah satunya.
Orang-orang mengatakan aku fobia pada pernikahan. Entahlah. Mungkin begitu, tapi mungkin juga tidak. Aku hanya bersikap rasional seperti juga waktu orang-orang menyebutku si spiritual eksperimentalis. Kalau sejak kecil aku selalu diajari bersikap rasional, kenapa aku tak boleh mengambil jarak serupa sewaktu mencintai seseorang atau saat aku berusaha menjalani ajaran agama yang kupilih dengan ikhlas dan hati gembira?
Bastian pernah bertanya padaku, apakah aku dibesarkan di keluarga berantakan. Tentu saja aku jawab tidak. Apa hubungannya? (kuejek dia yang mencoba menjadi Freud, mencoba menyelidiki masa kiniku dengan pengalaman masa kecil dan mimpiku).
Aku tidak lahir dari keluarga yang berantakan. Aku bukan anak hasil perceraian atau sejenisnya. Keluargaku normal seperti juga keluarga lainnya. Tapi apakah aku harus memaksakan diri, membeo seperti orang-orang yang melihat normal adalah kehidupan sehat dan sebuah pencapaian? Bagaimana orang-orang melihat pernikahan sebagai sebuah akhir padahal di mataku jelas-jelas itu sebuah proses tanpa final?
Kenapa menikah tidak dilihat saja sebagai sebuah pekerjaan (boleh main job atau side job terserah pilihanmu) dengan pembagian tugas jelas, target, namun tanpa deadline, berlangsung seumur hidup maksudku. Sampai aku mati maka aku harus bekerja untuk pernikahan itu.
Aku mengambil kesimpulan ini sesudah melihat ayah dan ibuku yang benar-benar tak pernah Lelah bekerja keras seumur hidup mereka untuk mempertahankan pernikahan. Mereka saling menyayangi, menyakiti, memuji, menghina, memeluk, memukul, mempercayai, membohongi, begitu terus seperti roda kendaraan yang berputar. Aku sungguh kagum pada kemampuan ayah dan ibuku bertahan hingga suatu hari kuputuskan aku tak mau repot-repot menjalaninya. Hidup itu pilihan kan. Ini tak ada urusannya dengan benar atau salah.
Namun, aku tak pernah mengatakan pada Bastian soal ini. Agama dan cinta adalah hal yang paling aku simpan rapi dalam hidupku karena aku tahu aku bisa tergelincir menjadi orang lain yang bukan diriku saat menghayati keduanya. Kusimpan rapat-rapat dalam laci. Bastian boleh ambil semua koleksi buku dan mainanku, kecuali dua hal itu.
Tapi, kuakui nasib buruk memang kadang tak bisa dihindari. Hidup yang kupikir akan berjalan lurus, ternyata memaksaku berbelok tajam hingga membuatku kebingungan sendiri saat aku memasuki usia 39 tahun. Tiba-tiba saja, di usiaku ini, aku kesulitan mengontrol hidupku.
Kejadiannya tiga bulan lalu. Setelah aku bertemu Bastian di sebuah kota yang bukan Jakarta dan juga bukan Solo. Kota yang harus netral, itu permintaanku ketika Bastian ingin bertemu denganku. Permintaanku yang kedua, kami harus meluangkan waktu minimal 24 jam lamanya agar bisa menghilang bersama. Dia setuju dan kami pun bertemu.
Seratus dua puluh jam bersama Bastian adalah pengalaman mengejutkan dan jauh dari kata membosankan. Aku ajukan satu hari dan dia meminta lima hari. Dia ternyata sastrawan yang tersesat, tersesat menjadi bankir maksudku, mengingat pengetahuannya tentang karya sastra Indonesia ternyata seluas Nusantara. Itu jelas membuatku yang jurnalis ini malu sendiri.
Aku tertawa waktu menulis itu di jurnalku yang entah bagaimana membuat dia tertawa juga. Aku menulis sambil terus tertawa di hadapannya sementara dia tiba-tiba minta jatah menulis juga. "Harus bergantian," kata Bastian menyeringai.
Seratus dua puluh jam bersama Nayanika adalah pengalaman mengejutkan dan membuatku sangat mual. Aku menaikkan alis saat membaca tulisannya.
"Kenapa mual, Bastian?"
Bastian tertawa terbahak. "Jiwa dan otakmu begitu dinamis, Nay. Aku seperti naik roller coaster. Sedikit mengerikan, tapi itu sebenarnya menyenangkan," kata dia.
Aku memeluknya spontan. Lama sekali sampai dia terbatuk-batuk. Entah kenapa kejujurannya membuat dadaku begitu hangat. Bastian adalah laki-laki yang baik.
Lalu segalanya terjadi begitu cepat. Mual yang dia rasakan tiba-tiba menular padaku.
Beberapa pekan setelah kembali ke Solo, aku juga merasa mual, pusing, muntah-muntah, lemas, hingga akhirnya terkapar di rumah sakit. Kupikir aku kecapaian. Namun, yang tak kuduga, wajah dokter di rumah sakit yang juga teman baikku justru tersenyum lebar ketika memeriksaku yang lemas di kamar.
"Siapa bapaknya, Nay? Kenapa kau tak pernah cerita?" tanya temanku itu yang membuat aku mendadak ingin melesak ke tanah saat itu juga.
Wajah Bastian tiba-tiba menyerbu ingatanku, bergantian dengan wajah seorang perempuan berkerudung di usia akhir 40-an yang sangat tradisional, lalu seorang remaja tanggung dalam sebuah foto keluarga. Bastian menyimpan rapi foto itu di salah satu ruang dompetnya. Beberapa kali dia bercerita dengan mata berbinar keluarga kecilnya yang tinggal jauh dari Jakarta itu.
Pikiranku berputar-putar lagi. Bayangan terikat pada satu orang saja sudah sangat menakutkan apalagi dengan tiga orang. Aku mengerang pelan. Bagaimana caranya agar aku dan bayi ini bisa lari dari Bastian?
Solo, 18 November 2022.
Ayu Prawitasari jurnalis, cerpennya telah diterbitkan di berbagai media
(mmu/mmu)